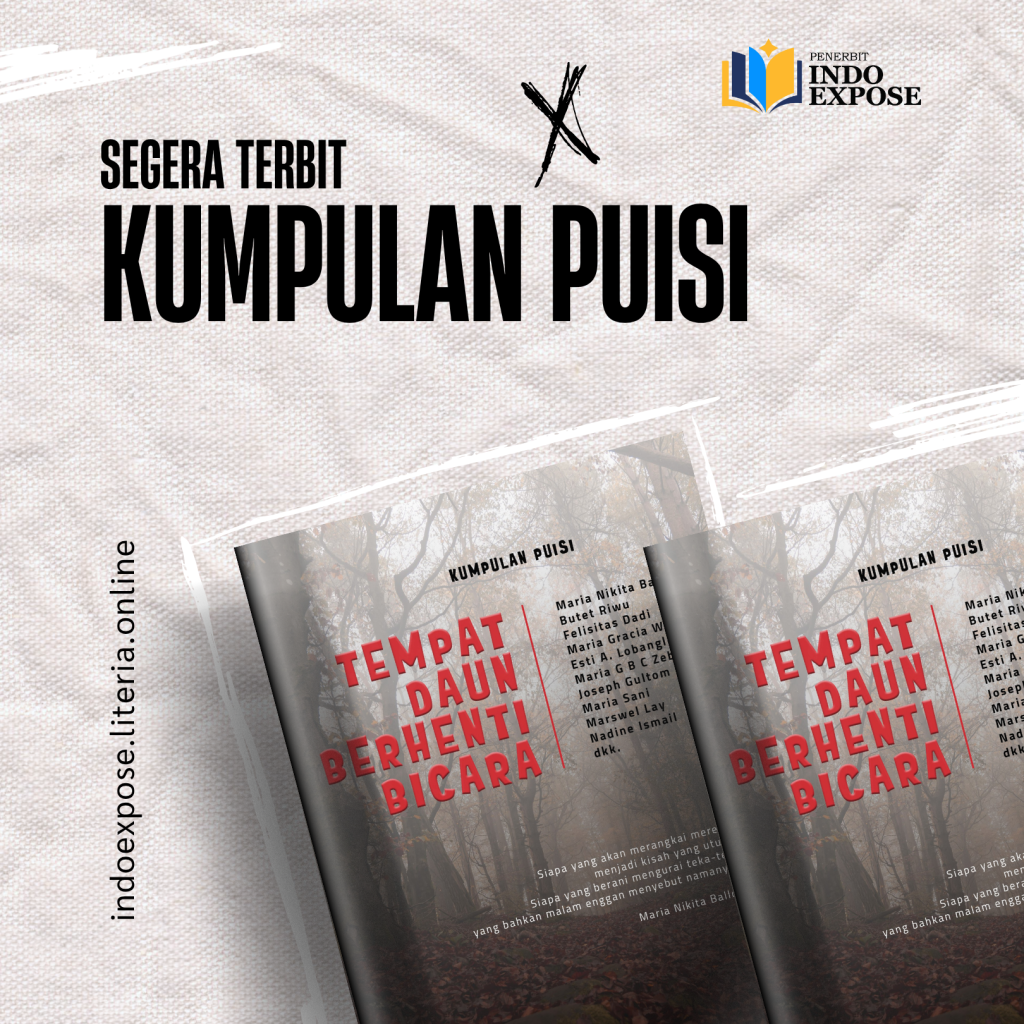(Review Buku Kumpulan Puisi TEMPAT DAUN BERHENTI BICARA)
Buku kumpulan puisi karya para penulis muda ini bukan sekadar antologi sastra. Ia adalah ruang eksistensial, tempat manusia muda belajar mengenali dirinya, sesamanya, dan dunia di sekitarnya melalui kata. Di sinilah kata tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi menjelma sebagai medium ontologis — wadah di mana keberadaan (being) manusia beresonansi dengan kehidupan. Sebagaimana Heidegger menegaskan bahwa bahasa adalah rumah bagi Ada, kumpulan puisi ini memperlihatkan bagaimana para penyair muda mulai membangun rumah makna mereka sendiri: sederhana, jujur, namun sarat kesadaran akan hidup yang lebih luas.
Dalam prolog RD. Drs. Stefanus Mau, Pr., pendidikan dipahami bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan tindakan pembentukan manusia seutuhnya — manusia yang berpikir, berperasaan, dan beriman. Dalam kerangka filosofis, pandangan ini sejalan dengan filsafat pendidikan humanistik yang dikembangkan oleh Paulo Freire dan Martin Buber, bahwa pendidikan sejati terjadi dalam dialog, dalam perjumpaan “Aku dan Engkau” yang saling menghidupkan. Maka, buku ini dapat dibaca sebagai dokumen pedagogis sekaligus spiritual: puisi-puisi di dalamnya menjadi cermin proses manusia muda menemukan “aku” mereka di tengah dunia yang terus berubah.
Analisis tematik terhadap puisi-puisi di dalamnya memperlihatkan tiga arus pemikiran yang saling berkelindan — eksistensial, sosial, dan ekologis.
Pertama, arus eksistensial tampak jelas dalam karya seperti Litani Lorong Gelap (Maria Nikita Ballo) dan Langkah di Persimpangan (Yohanes Jevon Suban Hera). Di sini, kita melihat pergulatan batin remaja yang berhadapan dengan kegelapan diri, ketidakpastian, dan pencarian makna. Mereka sedang, dalam bahasa Kierkegaard, berani menjadi diri sendiri di tengah absurditas hidup. Kegelapan dalam puisi-puisi itu bukan sekadar simbol penderitaan, melainkan medan transformasi: tempat di mana kesadaran dilahirkan. Ketika mereka menulis, mereka sebenarnya sedang melakukan fenomenologi pengalaman — menyingkap apa yang tersembunyi di balik keseharian, dan dengan itu menghidupkan kembali rasa takjub terhadap eksistensi.
Kedua, arus sosial hadir dalam karya-karya seperti Guruku yang Terhebat, Pendidik Sejati, Sahabat di Bangku Belajar, dan Teman Masa Depan. Puisi-puisi ini menggemakan nilai intersubjektivitas — kesadaran bahwa diri tidak bisa eksis tanpa orang lain. Dalam pandangan Buber, relasi sejati adalah relasi “Aku-Engkau”, bukan “Aku-Itu”; dan di sinilah para penyair muda memaknai peran guru dan sahabat bukan sebagai fungsi sosial, melainkan sebagai kehadiran yang menghidupkan. Pendidikan, dalam makna terdalamnya, menjadi ruang dialogis tempat kasih dan kebersamaan tumbuh — bukan sekadar ruang transfer informasi.
Ketiga, arus ekologis muncul dengan kuat dalam puisi seperti Tenangku, Lestarinya Bumiku, dan Alam Sahabatku. Para penulis muda ini menyuarakan kesadaran bahwa alam bukan sekadar latar kehidupan, melainkan mitra spiritual manusia. Dalam perspektif ekoteologi dan filsafat fenomenologis Merleau-Ponty, manusia dan alam memiliki hubungan timbal balik: tubuh manusia adalah bagian dari tubuh dunia. Maka, ketika mereka menulis tentang tanah, air, dan langit, mereka sebenarnya sedang menyapa dirinya sendiri — sebab manusia dan bumi saling mencerminkan. Kesadaran ini menjadi sangat penting dalam dunia modern yang sering kehilangan hubungan dengan alam, menjadikan pendidikan ekologis bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tindakan etis dan spiritual.

Struktur keseluruhan buku ini membentuk semacam narrative arc of becoming — perjalanan dari kegelapan menuju terang, dari keakuan menuju kebersamaan, dari keterasingan menuju kesadaran akan makna hidup. Ini sejalan dengan gagasan paideia dalam filsafat Yunani: pendidikan sebagai perjalanan jiwa menuju kebaikan dan kebenaran. Maka, buku ini bukan hanya dokumentasi karya sastra, tetapi jejak filosofis tentang bagaimana manusia muda bertumbuh dalam ruang simbolik yang penuh nilai.
Di balik bahasa yang sederhana, terdapat kedalaman ontologis: keberanian untuk mengungkapkan yang rapuh, memaknai yang biasa, dan meneguhkan yang tak terlihat. Puisi-puisi ini menolak kekerasan banalitas zaman yang serba instan. Mereka menjadi bentuk perlawanan halus terhadap dunia yang melupakan kontemplasi. Dalam pengertian ini, karya-karya tersebut berfungsi sebagaimana filsafat bekerja: mengajak manusia berpikir ulang tentang dirinya dan dunianya.
Akhirnya, Di Tempat Kata Menemukan Jiwa adalah sebuah perayaan kesadaran — kesadaran bahwa pendidikan, seni, dan iman tidak terpisahkan. Di sini, kata menjadi jembatan antara roh dan dunia, antara Tuhan dan manusia, antara harapan dan kenyataan. Membaca buku ini berarti ikut masuk dalam ruang sunyi tempat manusia belajar menjadi manusia, dengan segala keterbatasan dan kemuliaannya.